
Aku masih ingat betapa beratnya tas yang kugendong waktu itu. Ya. Tas merah bergambar Tamiya. Aku ingat betul, meski bukan berat tas itu yang terpenting, tapi akan aku ceritakan lebih lanjut.
***
Ketika aku duduk di kelas tiga Sekolah Dasar, belum begitu paham juga, kenapa Bu Jasmin gemar sekali menangis, dan parahnya, waktu itu aku tak tahu ia sedang menangis. Maksudku, bagi bocah kelas tiga, menangis haruslah mengeluarkan suara yang keras seperti aku dan teman-temanku yang lain bukan? Tapi, setelah aku tahu bagaimana seorang dewasa berpikir dan merasa, aku tahu, tangis dewasa dan tangis anak-anak itu berbeda. Sakit orang dewasa dan sakit anak sekolah sangat berbeda.
Ibu guru dalam cerita ini adalah satu-satunya pengajar di sekolah yang beberapa kali pernah kukuras cairan matanya dengan kebodohanku, barangkali. Satu air mata yang paling aku ingat adalah ketika itu, hari Ibu. Seperti kalian sewaktu belajar di sekolah, Bu Jasmin, guru bahasa kami, hari itu juga menyuruh semua murid mengarang tentang sosok malaikat tanpa sayap itu.
Rio, teman sebangku yang berkacamata menunduk, bungkuk, terlihat amat sibuk dan serius. Ketika aku melirik buku tulisnya, entah bagaimana dia, seperti bisa merasakan lirikanku, menutup buku tulisnya dengan tangan kirinya, melingkar, rapat seperti tubuh seekor kaki seribu perawan yang terancam dan, tetap menulis tanpa berhenti sejenak pun. Sedang setengah jam sudah berjalan, aku sendiri belum mampu menulis satu kata pun! Melamun suntuk juga tidak membuahkan hasil. Kutengokkan kepala ke belakang, ada tenda yang terbuat dari buku gambar berdiri tegak, siasat yang sama dengan Rio disusun oleh Anton. Untuk pengetahuan, Anton adalah temanku yang selalu menjadi musuh ketika bermain bola. Selalu! Karena dialah lawan suitku. Di sekolahku, cara membentuk tim sepak bola adalah dengan suit, pemenang suit akan satu tim dengan pemenang suit yang lain, dan sebaliknya.
“Sarapan apa si Rio ini, bagaimana bisa dia selancar itu?” tanyaku dalam hati ketika aku kembali melirikkan mata ke arah kiri.
Aku membayangkan Rio makan sepotong roti dan minum segelas oli. Oli? Tidak, tidak, itu mengerikan! Tetapi jika itu benar, mulai besok aku akan mengamalkan menu sarapan yang akan membuat isi kepalaku selicin Rio. Bapak banyak stok di garasi.
Bel istirahat pun berbunyi, seluruh kelas sepertinya sudah menyelesaikan tugas itu, hanya aku, bocah payah dalam hal mengarang, dan ketika kini aku mengingat kejadian tersebut, “bisa kok, dulu kamu mengarang cerita dan mengibul sedikit,” batinku, “sehingga kau tidak perlu melihat air mata Bu Jasmin itu.”
Ya, sungguh, ketika itu Bu Jasmin menangis karena aku tak bisa mengarang tulisan, tulisan apa pun itu untuk ibu.
Karena aku belum tahu seperti itulah pertanda orang dewasa sedang terluka hatinya, jadi aku bisa bodo amat dan keluar kelas untuk bermain seperti biasa. “Di mana Anton?” tanpa dia, aku hanya penghangat bangku cadangan!
***
Dengan iming-iming uang seribu, bapak menyuruhku membeli rokok. Ini masih cerita di waktu aku kelas tiga. Ini, juga cerita sebelum sesampainya aku di rumah dan dimarahi oleh bapak karena salah membeli. Bukan pulang dengan beberapa miligram nikotin, aku justru pulang membawa popok! Untungnya ibu membela. Tapi aku ingin melewatkan bagian yang ini, karena di sini, si pencerita sangatlah payah, lagi pula, ini bukan cerita tentangnya.
Sesungguhnya, itu bukan sepenuhnya kesalahan, maksudku, di sepanjang jalan menuju warung, pikiranku yang bocah selalu memikirkan Bu Jasmin tentang peristiwa tadi pagi yang membuat seharian tidak nyaman dan sulit berkonsentrasi, setidaknya sampai malam itu; ketika bapak menyuruh untuk kemudian berakhir sebuah bentakan mengerikan.
Ya. Sebelum tragedi malam itu, beliau, Bu Jasmin maksudku, kembali mengeluarkan air mata, tapi lagi-lagi perasaan dan pikiran bocah ini belum mampu menangkap sinyal itu. Aku cuma tahu, yang ada sikapnya jadi aneh.—Awalnya aku mengira Bu Jasmin hanya sedang flu. Aku juga begitu ketika flu, sering keluar air dari mata tanpa tahu sebabnya.—Kau harus tahu, tangis lirihnya berawal dari sebuah pertanyaan sepele yang dilempar kepadaku; intinya menyuruhku untuk menyebutkan nama pahlawan yang aku tahu. Dan sialnya, saat itu aku hanya asyik dengan penghapus baru yang aromanya wangi, tanpa bisa menyebutkan satu nama pun! Sehingga pecahlah sebuah tangis, tangis yang bukan dari seorang murid karena takut tidak bisa menjawab pertanyaan.
***
Malam ini, di kamar yang dingin, aku menulis cerita ini untukmu, sekarang aku sudah berusia 22 tahun. Artinya, ada seorang pemuda yang sedang teringat, meski samar-samar akan kenangan masa kecilnya. Keping-keping ingatan saling tumpuk dan berloncatan.
“Ibu Jasmin, harusnya aku menulis kata-kata untukmu waktu itu, ketika hari Ibu itu,” bisikku pada kesepian malam, “harusnya. Setidaknya aku menjawab pertanyaan itu dengan menyebut namamu, waktu itu.”
Dan sekarang, aku tahu perasaan Bu Jasmin. Tanpa terasa, air mata bagaikan embun pagi di pipiku yang daun ini.
Aku memutar searah jarum jam cangkir kopi beberapa putaran. Menjewer telinga wadah itu dan menikmati isinya. Merenung dan sejenak kemudian, meraih benda kotak bercahaya di sampingnya.
“Aku merindukanmu. Aku merindukanmu, Pahlawan,” ketikku dengan ponsel genggam baruku, enter, “karena sesungguhnya dirimulah pahlawanku di rumah dan di sekolah. Karenamu juga aku ada di dunia ini, Bu.” Lalu mencari kontak yang bertuliskan kata Ibuk.
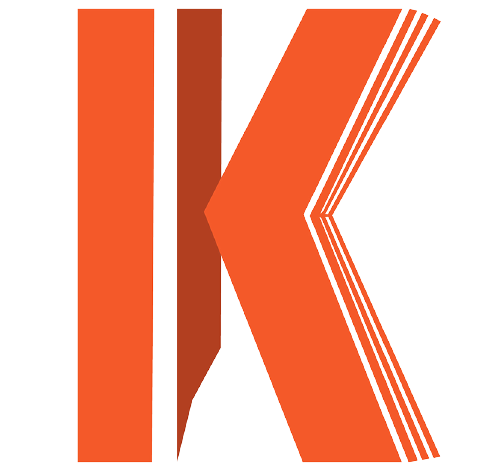
Keren cara bertuturmu, Dim.
Btw, rokok tertukar popok itu sungguh konyol. Haha
Sepertinya posmu ini mesti dibaca oleh Bu Jasmine
LikeLike
Hahahahah. Suwun, mas sudah mau berkomentar sepagi ini. Jangan lupa sarapan, ngopi juga, agar supaya fokus menjalani hari dan tidak salah mengucap rokok menjadi popok. Hehe.
LikeLike
Haha..
Siap siap
LikeLiked by 1 person
Bu Jasmin itu ibumu sekaligus gurumu? begitukah?
LikeLike
Yaaaaaa! Kira-kira begitulah ceritanya pak.
LikeLike
semoga ibunya baik-baik saja ya
LikeLike
Aamiin. Aamiin. Tengkyu banget pak narno.
LikeLiked by 1 person
Dari awal sampai akhir mengalir begitu mulus. Satu kata saja; menggigit!
👍🏻👍🏻👍🏻
LikeLiked by 1 person
Wah. Siap. Terima kasih jempol tiganya, Mas Andi. Lopyu!
Masih perlu banyak belajar (dan “bermain-main”) di prosa saya mas. Selamat pagi. 🙂
LikeLiked by 1 person
Lopyu too.
Yak betul jangan puas dan jangan ternakan pujian.
Selamat pagi juga.
LikeLike
Siiiiip.
LikeLike
Keren boskuuh
LikeLiked by 1 person
Terima kasih, bang. *Saliim. 🤟
LikeLike
kisahnya keren….daku terhanyut….
LikeLiked by 1 person
Terima kasih banyak, Mbak.
LikeLike