Darah muda darah yang berapi-api, kata Bang Rhoma Irama. Jika negara mematok tolak ukur kedewasaan secara administratif pada usia 17 tahun, maka bagi yang telah melewati usia tersebut, pantaslah mengenang apa yang terjadi sebelum umur itu tiba.
Dengan asumsi kebanyakan anak Indonesia masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun, maka ketika lulus SMA, mereka setidaknya akan berusia 17, 18 atau 19 tahun lebih sedikit. Saya kira keterlambatan sekolah bagi lumrahnya orang tua saat ini adalah sejenis aib – padahal mestinya tidak juga. Anggaplah anak SMA belum cukup dewasa, karena sebab batas usia tadi. Kebanyakan orang tahu bahwa masa SMA adalah masa-masa yang liar, romantis, sedikit kacau, namun kerap paling punya ikatan batin tersendiri di masa-masa mendatang.
Alkisah, saya tertakdirkan untuk jadi santri di sebuah pesantren yang cukup populer di Kota Malang. Mungkin dibandingkan dengan pesantren-pesantren Jawa Timur lain, jumlah santri jauh dari banyak. Namun di tengah banyaknya SMA, SMK maupun sekolah menengah swasta lainnya di Kota Malang, pesantren di kota Malang yang merangkap memiliki sekolahan tidak banyak. Pun lokasi pesantren semacam ini, banyak yang menepi dari pusat kota, karena di pusat kota sendiri berderet SMA-SMA pilih tanding yang dikenal masyarakat sebagai SMA Tugu – SMAN 1, SMAN 3 dan SMAN 4 – juga SMA-SMA lain yang banyak berdiri di pusat keramaian kota Malang.
Maka jelaslah Madrasah Aliyah pesantren tempat saya belajar mungkin tak sementereng MAN 2 Kota Malang (dulu MAN 3) yang kesohor itu, atau sesemarak MAN 1 di bilangan Tlogomas yang salah satu alumninya adalah gelandang top timnas Indonesia beberapa tahun silam, Ahmad Bustomi.
Tapi justru karena sekolah di pesantren, meski kadang kelihatannya terlalu serius sekolah atau mengaji, malahan jadwal melipir makan mie ayam atau tahu telor maupun sekadar ngopi bisa lebih banyak – sepanjang tidak terciduk oleh rekan-rekan keamanan.
Berbicara tentang masa SMA (atau lebih tepatnya MA) saya, maka saya tidak akan menafikan bahwa kami punya salah satu kelas paling mempesona sepanjang masa. Melihat rekam jejak generasi-generasi sebelumnya, memang hingga saat ini jumlah siswa IPA (kini konon disebut rumpun Ilmu-Ilmu Alam) di madrasah putra tidak terlampau banyak. Angkanya konstan sejak pertama dibuka: 8, 6, 7, 7, 5, 6, dan konon terakhir katanya ada 7 orang. Luar biasa.
Bukan berarti anak IPS jumlahnya sangat banyak. Kian kemari jumlah santri yang meneruskan sekolah dari Tsanawiyah hingga Aliyah kian sedikit, saya tak tahu mengapa. Gosip terakhir lulusan tahun lalu, jumlahnya hanya belasan. Entah merasa jadi korban atau bukan, saya kurang tahu seberapa signifikan pemisahan kelas antara Ilmu Alam dan Ilmu Sosial – dan di beberapa sekolah, dengan Bahasa dan Keagamaan. Toh nantinya tidak semua anak IPA memilih untuk meneruskan pendidikan di trek mereka, malah banyak yang menyeberang ke Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, atau malah Ilmu Al Quran dan Tafsir. Juga tak sedikit anak IPS, Keagamaan atau kejuruan non-teknik, yang menempuh pendidikan Teknik Informatika, Teknik Sipil, atau jurusan-jurusan sains terapan lainnya.
Madrasah Aliyah khusus putra di pondok kami belum lama berdiri. Saya dan kawan-kawan sendiri adalah generasi lulusan ketiga. Seingat saya dalam lulusan satu angkatan ada 36 orang: 30 santri IPS dan 6 santri IPA – termasuk saya.
Mulanya adalah penyaringan yang ditetapkan oleh dewan guru. Saya kira dulu ini ada kongkalikong tersendiri karena sistem rangking dan penilaian. Tersebutlah 12 siswa, dan di kenaikan kelas 11 MA, tinggallah 7 orang yang disertakan mengikuti program IPA oleh para guru. Ah, soal beginilah yang mulai memunculkan kesan anak IPA sekolahnya sulit.
Anda pernah dengar grup girlband Seven Icons? Tujuh gadis ini Anda tahu pernah menyanyikan lagu yang top pada masanya:
Gak-gak, gak kuat
Gak-gak, gak kuat
Aku gak kuat, sama playboy gampangan.
Demikianlah kami bertujuh terdampar di kelas. Tujuh orang pemuda tanggung, yang masing-masing punya alam pikirannya sendiri, dan tentu saja nyaris tiap orangnya sedang terjebak romansa masa muda.
Sebut saja yang pertama Rohman. Konon berdasarkan gosip santriwati kala itu, setiap dibincangkan ia mesti disebut “Si Rohman yang ganteng tuh…” sebagai embel-embelnya. Wajahnya mulus, kuning langsat, tidak terlalu Chinese, berkumis tipis, bentuk wajahnya bulat belaka. Dia gandrung pada soal-soal biologi – dan juga gandrung dalam teori-teori cinta, dan saya sebagai anak yang polos sering menjadi korban. Di kelas, konon ia yang paling tampak berpengalaman.
“Jadi begini, Bal. Tak kandhani. Kalau suka cewek itu kamu mesti begini…” Dan sisa selanjutnya hanya teori.
Rohman yang rumahnya sekitar 1 jam perjalanan motor dari pondok, adalah ketua kelas kami kala itu. Tentu karena tipikalnya yang agak berkesan dewasa, lebih tenang dari kami, namun mungkin kala itu belum pandai menyembunyikan kekecewaannya kepada orang. Ah, anak muda memang suka panas sendiri kadang-kadang.
Sayang, di kelas 2 MA ini ia mesti keluar dari pesantren. Sejak masuk sekolah di tingkat Tsanawiyah, ia memang cenderung sakit-sakitan. Matanya sering kuning, nyeri perut, dan tetiba pingsan. Kondisi ini menyebabkannya makan sangat teratur – yang jelas bukan karakteristik kebanyakan santri, dan untuk beberapa waktu sangat sering sekolah pulang pergi dari rumah. Beberapa orang mencibir kebiasaannya ini karena dipandang hanya sekadar alasan saja.
“Ah, Rohman ini sakit dibikin-bikin. Toh dia tetap saja di rumah pacaran, SMS-an sama santriwati.” kata orang-orang seperti ini. Saya kira pendidikan empati memang hal sulit yang perlu diajarkan di mana saja.
Saya tidak tahu kabar terkininya. Sudah lama sekali kami tak bertemu. Terakhir kali adalah suatu hari di masa liburan, saya diajaknya menginap di kontrakannya area bilangan Telkom Kota Malang di daerah Blimbing. Ia kuliah di salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi kenamaan di kota Malang. Di kontrakan itu, ia rupanya cenderung dituakan. Saya juga dikisahkannya soal bagaimana ia bertungkus lumus di kampus menghadapi orang-orang yang tak becus.
Satu hal, ia adalah orang yang punya kecenderungan gandrung pada hal spiritual – jika tak ingin saya sebut mistik. Membaca kepribadian orang dari sekadar bertemu – yah, meskipun memang ada ilmunya –, membuka mata batin, atau mengamalkan tarekat-tarekat tertentu. Saya mendadak diterawang olehnya: benar saja, ia berkata ada yang kosong dalam jiwa saya.
Tentu saja saya hanya bisa mengiyakan – toh setiap orang punya sisi kosongnya, baik dari masalah percintaan, ekonomi, atau mungkin rohaniah. Dan demikianlah pertemuan terakhir saya dengan Rohman.
Selanjutnya adalah Fauzi. Oleh kawan-kawan, ia dipanggil Ayam – mungkin karena agak manyun mulutnya, dan cenderung kurus. Ia adalah anak IPA yang paling jago main bola. Kecerdasannya yang paling menonjol adalah dalam matematika – dan dia adalah rujukan saya. Tidak ada yang bisa menyelesaikan trigonometri, matriks, atau integral secara mumpuni dibanding dia di kelas.
Untuk menuju ke rumahnya, mungkin tak sampai 1 kilometer dari pesantren. Cukup menyusuri rel kereta api, belok sedikit, sampailah. Ia sempat kuliah di jurusan Pendidikan Matematika di sebuah kampus swasta di Malang. Namun, ia menjebolkan diri. Rupanya ia mendaftar sebagai analis laboratorium di Pabrik Gula, yang lokasinya tak jauh dari pesantren kami, dan tentu saja dekat dengan rumah Fauzi. Hebatnya, ia lolos dan mampu mengungguli sarjana-sarjana lain yang melamar – ia hanya mengandalkan ijazah lulusan Madrasah Aliyah. Kini ia sudah menikah, dan sedih sekali saya tak sempat menghadiri momen itu.
Kemudian Udin. Ia adalah gambaran kecerdasan bahasa yang begitu khas: ia suka menyanyi, rajin, dan bisa mengerjakan persoalan-persoalan menjadi lebih mudah. Kami berdua sekelas di sekolah dan madrasah. Bersama saya, kami berdua beruntung mendapatkan santunan beasiswa dari pemerintah. Ia sudah selesai dengan kuliahnya, dan saya belum.
Penampilannya sangat layak di-ustadz-kan. Secara ilmu agama (maksud saya dalam persoalan penguasaan dan hapalan teks agama, serta penguasaan bahasa Arab) saya rasa dia hebat sekali. Dia rajin menghapal Al Quran dan perkataan ulama, membacanya, dan saya tak henti-henti terpukau dengan konsistensinya dalam bersikap. Saya yang lemah dalam hapalan tentu sangat bangga dengan teman semacam ini.
Orang keempat: Ardi. Pemuda yang sangat galau. Menjadikan penampilan pria Korea sebagai model rujukan. Rambutnya: ditepikan ke samping secara maksimal, dicukur tipis di bagian pinggirnya. Saya masih ingat motornya setelah lulus: motor cina warna kuning menyerupai Satria FU namun dari pabrikan Happy, sering ngadat, yang tidak bisa ditekan tombol starter-nya, sehingga mesti menginjak tuas dahulu untuk dinyalakan.
Informasi yang saya dapat soal keberadaannya pasca lulus sekolah tidak cukup klir. Ada yang menyatakan ia kuliah di jurusan Teknologi Informasi; ada yang menyebutnya kuliah jurusan bahasa Inggris; ada yang menyatakan bahwa ia masih jadi pemuda galau. Tapi sepertinya kian kemari keberadaannya cukup jelas, ia menjadi pendidik Pramuka di beberapa sekolah dan kampus. Terakhir, ia saya ketahui kuliah di salah satu kampus agama Islam ternama di Kabupaten Malang.
Lalu sosok kelima adalah Mufa. Bakatnya paling menonjol adalah seni menulis indah – dan memang bentuk tulisannya bagus, bidang tarik suara yang membuatnya mendapat panggung dalam gelaran-gelaran kasidah dan hadrah, serta bahasa. Kabar terakhir ia sudah menyelesaikan kuliah jurusan pendidikan bahasa Arab di salah satu kampus negeri di Malang.
Jika Anda pernah berkunjung ke blog saya, Anda dapat merujuk posting berjudul Cerpen. Saya menyertakan bahwa ada orang yang meminta untuk dibuatkan surat cinta. Mufa pernah gandrung dengan seorang gadis – yang kini sudah menikah dengan orang lain – dan saya diminta membuatkan surat dengan narasi-narasi dari lagu Armada. Sedihnya saya tak pernah membuat surat serupa untuk tujuan-tujuan saya sendiri.
Sebelum beranjak ke orang keenam dan ketujuh – tulisan dari Ikatan Kata ini mensyaratkan sekurang-kurangnya tujuh orang yang dideskripsikan – izinkan saya menyatakan bahwa kami menetap di kelas yang paling kecil dibanding kelas-kelas yang lain. Tentu terasa luas bagi 8 orang. Kursinya disusun bentuk huruf U, sehingga semua mata tertuju pada kursi guru yang diletakkan di tengahnya.
Wali kelas kami sedari kelas 10 sama belaka, guru paling cemerlang dalam urusan matematika. Soal-soal buku Erlangga yang rumit, bisa mudah dituntaskan olehnya. Ia sangat perhatian, tidak pernah menunjukkan gelagat membenci, dan dengan murid-murid yang tidak bersemangat pun, beliau tetap berkenan masuk kelas, memberikan satu dua materi dengan cara termudah.
Dulu sempat kami punya wali kelas guru biologi, tapi saat ini sudah tidak lagi mengajar di sekolah kami. Agaknya beliau sibuk di luar, namun terlepas dari sikapnya yang pernah cukup tajam pada kami anak-anak didiknya karena mungkin kelewat disiplin, ia punya jasa besar buat saya secara pribadi: memberikan surat rekomendasi beasiswa untuk salah satu kampus swasta kecil di Jakarta, yang terkenal karena pendirinya adalah orang besar dan berisi gagasan besar. Yap, kampus Paramadina namanya.
Meski sudah dapat rekomendasi dari guru, dari kepala sekolah, kritikan datang dari banyak orang. Karena persoalan aliran, soal pergaulan, dan sebagainya dan lainnya. Bahkan saya sempat disodori satu novel yang berisi sindiran tajam soal kampus dan isi pendidikan di dalamnya. Ibu saya begidik ketika membaca novelnya, tapi Bapak saya tertawa-tawa. Dan meski jadi mendaftar dan rasanya sangat berdarah-darah menyiapkan berkasnya, saya tidak lolos. Karena itulah di tengah beberapa guru atau ustadz yang kurang berkenan memberikan rekomendasi, guru dan kepala sekolah bisa memfasilitasi gelora muda saya.
Selanjutnya orang keenam, Ruli. Kini ia sudah punya aset bisnis yang bukan main: empat kedai kopi, satu jasa konveksi kecil-kecilan, serta dirinya sebagai penyedia jasa kelola data. Karirnya menanjak sejak di kampus. Konon, ia terlibat dalam banyak hal – berdasarkan kisah saat kami bertemu di Cibinong setahun lalu. Ia bekerja sebagai teknisi IT di salah satu ritel ternama di sana. Pengakuannya, ia pernah menjadi asisten dosen, pegawai rektorat, punya asisten pribadi di kampus, wah mentereng sekali.
Mungkin bagi sebagian orang seperti membual, tapi asetnya saat ini di beberapa tempat sepertinya menunjukkan bahwa tekad dan ambisinya bukan isapan jempol. Dulu kawan saya ini sangat bercita-cita jadi dokter, karena itu ia sangat gandrung pada biologi. Ia sering menceritakan pada saya soal bahwa ia ingin jadi dokter. Semua jalur ia coba, dan rupanya belum ada yang tembus. Mungkin realistis dengan usia atau mungkin ada orang yang memberinya sedikit pencerahan, ia beralih ke arah teknologi informasi. Semasa kuliah, ia mengembangkan pendeteksi kesuburan tanah dengan algoritma tertentu, dan skripsinya ini dimuat di koran lokal. Luar biasa.
Memang ia sangat berapi-api – saya sering ketularan apinya. Tanpa gelagat dia yang kelewat berlebihan, mungkin kami tak akan bikin mading yang mahal dan bagus, tapi kandas – karena mungkin ambisi Ruli ini sudah sedikit bergeser ke hal lainnya. Saya jadi tak punya saluran untuk menulis untuk waktu yang cukup lama. Sebelum mading muncul, ia mengajak saya untuk menghidupi perpustakaan pondok – meskipun akhirnya gagal lagi. Namun gara-gara dia juga, kami berdua plus dua santri putri senior mendapat pelatihan gratis di Perpustakaan Umum Kota Malang tentang literasi, pengelolaan perpustakaan, dan media untuk sekolah dan pesantren.
Saya akan mengenangnya sebagai salah satu orang yang membuat saya berpikir bahwa ambisi dan cita-cita itu penting di awal. Meskipun mempertahankannya tentu lain soal.
Terakhir, tentu saja saya sendiri. Di kelas mungkin bukan yang paling cemerlang, bukan yang paling punya kisah romansa, payah dalam olahraga, tapi setidaknya saya akan mengenang kawan-kawan di kelas kecil kami ini, lalu menertawakan masa muda kami yang konyol, sering berkonflik, kadang rukun, sering galau dan gelisah. Sengaja saya memaparkan diri sendiri sebagai teman, karena menurut para filsuf eksistensialis, diri dan identitas adalah hal yang sama sekali berbeda. Identitas dibentuk oleh konstruksi sosial dan lingkungan, namun kedirian dan hal-hal paling asasi dari manusia, seperti hasrat, beragama, atau berpikir, adalah perwujudan bahwa manusia itu ada. Dan mungkin saya mesti mengakrabi identitas dan diri saya sendiri, sebagai teman terdekat yang akan selalu ada bersama saya.
Tulisan ini masih sekadar mengulas kawan-kawan sekelas. Belum lagi kawan-kawan seangkatan, waduh, bisa satu buku sendiri sepertinya. Tidak ada beda kelas IPA dan IPS: sama-sama konyolnya di masa lalu. Hal yang membedakan kami saya kira hanya jadwal les jelang UN saja, selebihnya: ngopi, ghibah, senda gurau, atau membayangkan hari depan yang tak pernah pasti, pikiran anak IPA dan IPS sama saja.
Masa muda, masa yang aneh-aneh. Mengutip lagu populer Hivi!:
Indahnya kisah kasih di masa remaja…
– Ketik#7: My Circle disponsori oleh Ikatan Kata.
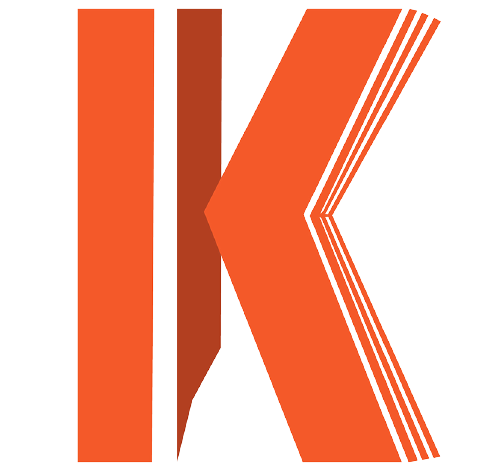
Masa muda…,,,tarikkk,😄
LikeLike
Bu Sondang lebih tahu dulu soal anak muda sepertinya. 😄
LikeLiked by 1 person
Khan pernah muda juga he he he
LikeLike
Kalau soal muda sepertinya Ibu Sondang pernah muda lebih dulu dari saya 😅
LikeLike
Bal, sisipkan MORE di pos ini
LikeLike
Sudah pak, tadi terlewat semangat. 😁
LikeLike
Kalau pas reunian sama ketujuh temanmu ini pasti bakalan seru ya, Bal.
LikeLike
Wah, bisa jadi kang 😁
LikeLike
Kisah klasik untuk masa depan.
LikeLike